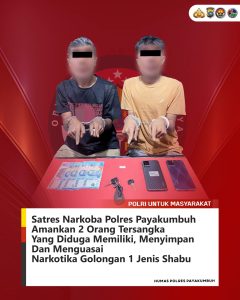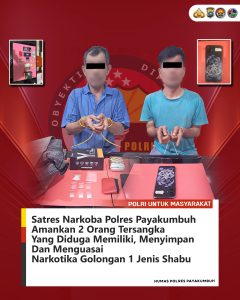Penulis: Kombes. Pol. (Purn) Robinson Simatupang, S.H., M.Hum
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
Sumbar24jam.com|Medan – Derasnya Kasus, Krisis Integritas Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi ironi besar dalam perlindungan anak. Meskipun negara telah melahirkan berbagai regulasi progresif – mulai dari Konvensi Hak Anak (diratifikasi lewat Keppres No. 36 Tahun 1990), UU SPPA No. 11 Tahun 2012, UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, hingga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 – angka kekerasan terhadap anak justru menunjukkan tren meningkat.
Kasus-kasus yang mencuat ke permukaan, membuktikan: Pertama, Eks-Kapolres Ngada menjadi tersangka kekerasan seksual terhadap tiga anak, dengan modus mengunggah video asusila di situs daring [Tempo/Kompas, 2025]. Kedua, Kasus Tenaga Pendidik di Sebuah Pesantren yang mencabuli 13 Santriwaati [Komnas Perempuan, 2025]. Ketiga, Kasus Anak Disabilitas yang diperkosa di Jakarta Timur, sempat dikira hilang [Detik.com, 2025]. Ketiga, Kasus Seorang Polisi sebagai Terdakwa di Papua, divonis bebas oleh hakim [BBC Indonesia, 2022].
Belum lagi, Kasus M. Azis Nasution di PN Pakam No. 344/Pid.B/2025 memperlihatkan ironi lain: seorang ayah dihukum karena merusak handphone milik anaknya, yang sebelumnya terpapar konten pornografi homoseksual. Alih-alih melihat konteks perlindungan anak, hakim hanya menggunakan pendekatan positivistik sempit — seperti memakai kacamata kuda — dengan fokus pada unsur tindak pidana pengrusakan barang, padahal itu merupakan bentuk kekecewaan ayahnya kepada anaknya yang terpapar konten pornografi, sehingga handphone tersebut dihancurkan guna memisahkan handphone dengan si anak.
Hal ini tentunya, mengabaikan rasa keadilan masyarakat dan kemanfaatan hukum bagi perlindungan anak. Hakim sepatut dan selayaknya membebaskan si ayah dari anak tersebut, namun sayangnya hakim memutus pidana penjara selama 2 bulan kurungan terhadap si ayah sebagai terdakwa.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Apa yang salah dengan sistem perlindungan hukum pidana anak kita?.
Bagaimana mungkin aparat yang seharusnya menjadi pelindung justru berubah menjadi predator, dan hukum malah menjadi alat yang melukai keadilan substantif?.
Data Nasional: Lonceng Darurat
Berdasarkan Data Perlindungan Anak KPAI 2024, tercatat 3.536 kasus kekerasan terhadap anak pada 2024. Kekerasan seksual menempati porsi terbesar, yaitu 41,2% dari keseluruhan kasus. Sementara itu, menurut Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2021, bahwa: 1 dari 17 anak mengalami kekerasan seksual; 1 dari 7 anak mengalami kekerasan emosional; dan 1 dari 10 anak mengalami kekerasan fisik. Ini bukan lagi sekadar masalah sosial — ini kegagalan sistemik dalam perlindungan hukum terhadap anak.
Analisis Kebijakan Kriminal Anak dalam Krisis
Dalam kerangka kebijakan kriminal, sebagaimana ditegaskan oleh Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah “seni dan ilmu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan melalui sarana yang rasional, baik penal maupun non-penal, dengan tetap berlandaskan pada penghormatan hak asasi manusia” (Ancel, Social Defense: A Modern Approach to Criminal Problems, 1965).
Mengacu pada pemikiran ini, Indonesia secara yuridis memang telah membangun arsitektur perlindungan hukum anak melalui berbagai instrumen legislasi, seperti Konvensi Hak Anak (Keppres No. 36/1990), yang diundangkan untuk menjamin hak hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan. UU SPPA No. 11/2012, mengutamakan keadilan restoratif bagi anak sebagai pelaku, namun juga mempertegas perlindungan terhadap anak sebagai korban. UU Perlindungan Anak No. 35/2014, memperluas definisi kekerasan terhadap anak dan mempertegas sanksi pidananya.
UU Penyandang Disabilitas No. 8/2016, menegaskan hak perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dan UU TPKS No. 12/2022, memperkuat instrumen hukum melawan kekerasan seksual. Namun, jika ditinjau dalam perspektif kebijakan kriminal menurut Ancel, implementasi sistem hukum tersebut belum sepenuhnya mengaktualisasikan prinsip perlindungan maksimal terhadap anak sebagai kelompok yang rentan.
Anomali yang terjadi—lemahnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum, terjadinya kejahatan oleh oknum aparat sendiri. Kasus Kapolres Ngada membuktikan bahwa bukan hanya masyarakat sipil, aparat sendiri dapat menjadi pelaku — merusak kepercayaan publik secara struktural.
Fragmentasi koordinasi antar lembaga, Polri, Kejaksaan, LPSK, UPT PPA, masih minim. Sistem informasi perlindungan anak belum terpadu. Hingga krisis budaya hukum— menunjukkan bahwa kebijakan kriminal nasional masih dominan berorientasi formalistis, bukan substantif. Perlindungan anak seringkali dianggap sekadar formalitas, bukan panggilan moral dan konstitusional.
Dalam kerangka kebijakan kriminal yang ideal, sebagaimana diajarkan Ancel, perlindungan anak tidak cukup diwujudkan dalam regulasi saja, tetapi harus diintegrasikan dalam sistem pengawasan efektif, seleksi ketat aparat, reformasi budaya hukum, dan penguatan koordinasi lintas sektoral.
Perlindungan anak harus menjadi nilai luhur yang menjiwai seluruh kebijakan dan tindakan aparat negara, bukan sekadar slogan hukum belaka.
Sudah Saatnya Menempatkan Anak sebagai Subyek Hukum yang Seutuhnya
Kondisi ini menjadi alarm keras bagi Indonesia sebagai bangsa, bahwa anak-anak bukan hanya penerima perlindungan secara pasif, melainkan pemegang hak konstitusional yang harus diakui dan dihormati secara utuh dalam setiap aspek kehidupan. Sebagaimana ditegaskan dalam teori kebijakan kriminal oleh Marc Ancel, perlindungan terhadap masyarakat, termasuk anak-anak sebagai kelompok rentan, tidak cukup melalui perumusan hukum positif saja.
Kebijakan kriminal yang efektif harus mencakup pendekatan rasional, berimbang antara sarana penal dan non-penal, dengan berlandaskan pada penghormatan mutlak terhadap Hak Asasi Manusia. Sehingga, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (The Best Interest of the Child) tidak bisa hanya menjadi slogan normatif. Maka prinsip tersebut: Pertama, harus menjadi standar etis dalam setiap tindakan penyidikan, penuntutan, peradilan, dan perlindungan sosial.
Kedua, harus menjadi pedoman absolut dalam pembentukan kebijakan dan pengawasan internal aparat penegak hukum. Negara, melalui seluruh instrumennya, harus menginternalisasi bahwa pelindung utama hak anak bukanlah sebatas teks undang-undang, melainkan integritas moral, profesionalisme hukum, pengawasan efektif, serta budaya penghormatan terhadap martabat anak manusia. Transformasi budaya hukum — yang berorientasi pada perlindungan anak secara holistik — merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan negara benar-benar berakar pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak anak, sebagaimana prinsip fundamental dari kebijakan kriminal modern.
Biography
Robinson Simatupang adalah seorang purnawirawan perwira menengah Polri dengan pangkat terakhir Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol.) Beliau memiliki pengalaman panjang di bidang penyidikan dan penegakan hukum, termasuk dalam menangani kasus-kasus sensitif yang berkaitan dengan perlindungan anak. Saat ini, beliau tengah menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH-USU) dengan fokus penelitian pada reformasi sistem penyidikan pidana nasional.
Melalui tulisan dan keterlibatannya dalam diskusi akademik, Robinson berkomitmen untuk mendorong perbaikan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) dan hak asasi manusia secara umum. (Tim)
![]()